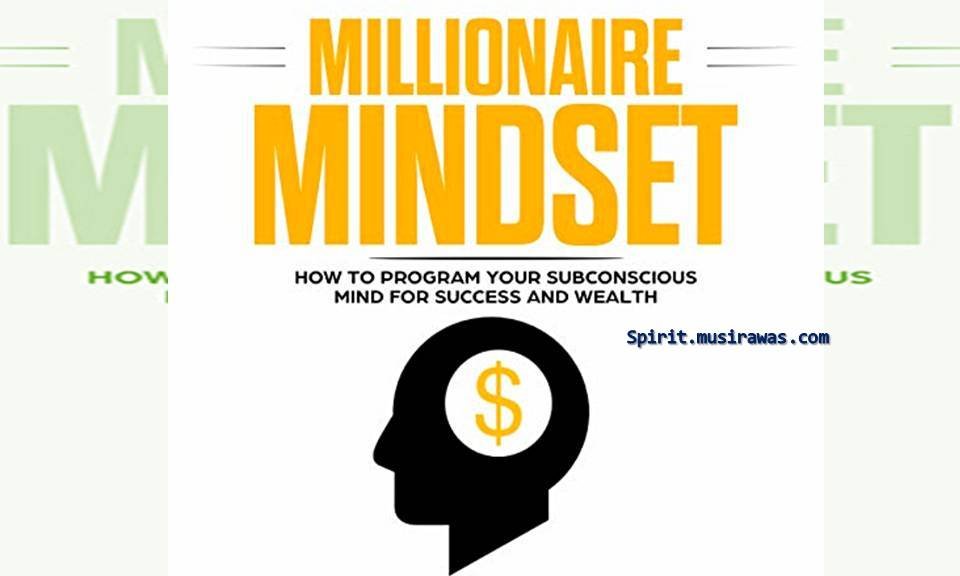Baca Tulisan Sebelumnya : Otak Sama, Nasib Beda?
DULU kehidupan saya mengalami goncangan yang amat sangat. Itu bukan pertama kali melainkan kedua kalinya saya terpuruk. Tapi yang kedua itu sangat dahsyat, seluruh harta saya hilang dan utang saya juga bertumpuk.
Ketika itu saya memiliki beragam bisnis, tetapi dalam masa hampir bersamaan “shit happened” alias kesialan beruntun terjadi didalam kehidupan saya. Money changer saya kecurian hingga 2 kali dalam 3 bulan. Kapal Barge saya yang bertransaksi dalam pengiriman ke Kenan Equatorial Mining di BalikPapan, karam dan asuransi tidak membayarnya.
Pabrik Kapur Hydrated Lime saya yang masih berutang ke bank kena gempa di Cileungsi. Gempanya memang kecil, tetapi meretakkan tungku utama dengan harga yang mahal. Traktor di quarry kapur meluncur tak terkendali, menabrak silo di pabrik, asuransi juga tidak menggantinya.
Baca : Sadar Kaya (Prakata)
Ditambah bank pembiayaan PDFCI ditutup BPPN. Ditengah krisis berkepanjangan, harga bahan baku naik 200%, yaitu gas. Perusahaan saya terpaksa “file for bankruptcy.”
Semua musibah ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu pada 1999 – 2001. Kerugiannya tak tanggung-tanggung, mobil 4 habis, 1 rumah hilang sedangkan utang masih 9 digit!
Setiap saat, setiap hari, emosi saya memuncak. Makan keluarga, bayar sewa, uang sekolah anak, membuat panik dan marah. Mau bekerja dimana? Kapan utang terbayar? Bagaimana untuk hidup?
Dikejar debt collector, dikejar hukum, dikejar BPPN, dan dikejar teman investor yang marah dan kecewa. Bayangkan Betapa kusutnya situasi saya saat itu.
Ditengah keputusasaan, siang itu saya langsung memandang langit dan bicara langsung kepada Allah SWT., Tuhan yang saya percayai 100%. Saya katakan bahwa saya putus asa dan hidup saya sudah diambang frustasi. Saya marah sekali kepada semuanya. Saya menuduh kehidupan ini tidak adil.
Saya merasa telah melaksanakan seluruh ajaran agama. Saya teringat betapa tertibnya saya melaksanakan puasa Senin-Kamis selama 5 tahun, tak terputus. Setiap malam, saya selalu bangun untuk bertahajjud. Yang wajib-wajib apalagi, sudah pasti saya laksanakan.
Hitungan zakat maal dan sedekah lainnya, saya bayarkan lebih dari 2,5 persen aturan baku. Saya mendirikan panti asuhan dan mengelola 8 panti lainnya, menampung 400 anak yatim dalam kurun waktu 5 tahun. Itu semua saya laksanakan dengan tulus dan keindahan munajat.
Namun, ketika kebangkrutan beruntun selama 2 tahun tanpa jeda dan tanpa belas kasihan terjadi kepada saya, saya mempertanyakan apa bukti ketaatan dengan kenyataan yang saya dapat?
Jujur saja, saya marah kepada Tuhan. Saya protes. Bahkan, sempat muncul keraguan dalam hati saya yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Saya bertanya kepada-Nya, mengapa musibah ini menimpa saya?
Apa lagi yang kurang dari saya, sehingga saya pantas menerima ini semua? Mengapa rasanya hidup ini kejam dan sadis sekali? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam kepala saya.
Akhirnya saya mulai menjauh dari Tuhan. Jangankan yang sunat, yang wajib pun saya tinggalkan. Saya meragukan semuanya tentang ajaran kebenaran agama saya. Saya diam, saya bertanya tak ada jawaban, saya kesal, saya murka.
Permasalahan ekonomi ini akhirnya berimbas pada rumah tangga dan pernikahan pertama saya yang dulu. Istri saya kembali ke rumah mertua. Kemudian saat itu anak saya yang tertua demam, panas tubuhnya 39 derajat celcius dan sudah tak bisa bangun. Adiknya pun mengalami hal yang sama. Mereka masih balita, berusia 4 dan 2 tahun.
Listrik dirumah sudah dipadamkan PLN, tidak ada lagi makanan, tidak ada uang ditangan, dan setiap saat ada telpon dari penagih utang-utang saya. Saya berutang pada lebih dari 5 institusi keuangan dan lebih dari 60 individu. Dari yang utangnya sejumlah 1 juta hingga miliaran.
Puncaknya, suatu hari saya ditelepon oleh seorang pemberi utang yang mungkin dia sudah muak dengan saya. Dengan kasarnya dia bilang akan mendatangi rumah saya sore itu dan dia akan menagih hutang. Kalau tidak dibayar maka dia akan paksa. Gaya bicaranya sudah seperti preman. Tumpah darahpun dia siap, katanya.
Saya tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengasah pisau. Saya sudah tidak sanggup lagi dan bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau memang orang itu menentang pertumpahan darah, terpaksa saya melawan. Saat itu rasanya saya siap membantai orang. Saya sudah tidak peduli lagi akan apa yang terjadi. Saya sudah tidak punya apa-apa, bahkan harga diripun tidak ada. Saya siap mati.
Kedua anak saya yang demam, membujur lemas di lantai beralaskan bedcover. Yang satu minum dari botol air tajin beras, yang satu hanya diam dengan botol air mineral yang tidak diminumnya. Saya hanya menatap kosong. Ke dokter tak bisa, jalan tak bisa.
Karena itulah, begitu ada yang menentang harga diri saya yang sudah tidak punya apa-apa ini, saya siapkan jiwa raga. Dia yang menagih kalau datang mencari ribut, akan saya bunuh! Ya, pikiran laknat itu sempat terlintas dalam benak saya.
Saat itu saya berfikir, toh dia orang rantau. Keluarganya tak ada dikota ini, temannya pun pasti tak banyak. Kalau saya terpaksa harus membunuh dia, akan saya kubur dia di halaman belakang. Tidak akan ada yang tahu. Rasanya saya benar-benar dirasuki dajjal.
Saya kumpulkan barang-barang yang sekiranya bisa saya pakai membantai orang. Benda tajam, benda keras, benda panjang, semua senjata serang. Saya tahu sekali bagaimana menggunakannya, dan tahu sekali dimana letaknya disetiap sudut rumah.
Kring…. kring…. kring…. telpon rumah yang sudah di blokir yang hanya bisa menerima panggilan itu, berdering. Sementara saya masih melamun dengan gamang. Hingga dering kesekian, barulah saya tersadar. Mungkin itu si penagih utang lagi, pikir saya. Dengan gusar, saya pun mengangkat telpon.
“Halo!” kata saya, dengan kasar.
“As salamu alaikum mas,” kata suara diseberang dengan lembut. Saya mengenalinya sebagai suara pak Aly, Pimpinan Yayasan Husnul Khotimah yang kemudian dikenal sebagai Rumah Yatim Indonesia, Panti Asuhan yang saya bangun.
Sayapun terhenyak dan menjawab dengan melemah, “Wa alaikum salam, pak Aly.”
“Mas, saya telepon sampai 3 kali, kok gak diangkat? Lagi sibuk, Mas?” tanya pak Aly dengan logat Lamongan-nya yang khas.
“Maaf pak Aly. Saya sedang ada kesibukan. Apa kabar?” sahut saya dengan mengatur napas yang sedang emosi.
“Mas, dengar-dengar sedang ada masalah, ya? Istri pergi, anak sakit, rumah dan isinya sudah dijual, listrik diputus. Apa benar mas?” tanya-nya dengan serius.
Dengan berat saya menjawab, “Ya benar, pak Aly.”
“Mbok ya kalau ada masalah begini ceritalah ke saya Mas,” kata pak Aly.
Saya tertegun mendengar kalimatnya.
Kemudian lanjutnya, “Mas, walaupun kita miskin, yayasan kita ada sedang pegang uang. Kalau Mas butuh, ada nih 3 juta. Pakai saja dulu Mas. Mas berhak, kok. Sudah 5 tahun Mas membangun yayasan ini, kalau ada masalah seperti ini, Mas punya hak untuk memakai atau meminjamnya. Mas. Saya kerumah sekarang ya, biar Mas bisa bawa anak-anak ke dokter, saya antar.”
Nyeeesss….. Rasanya saat itu bara dihati saya seakan disiram seember es batu. Saya tertegun, terduduk dan menangis tersedu-sedu. Saya tak kuasa menahan getaran didada, antara haru , malu, senang, kesal, semua jadi satu.
Dengkul saya keduanya dilantai, tangan kanan saya masih memegang klewang – pedang pendek – yang terasah tajam. Sesaat kemudian saya buang jauh. Yang ada hanya diri saya yang tersungkur bersujud. Saya salah, saya salah, saya salah ….., bathin saya memohon taubat.
Tak lama kemudian, selagi saya terduduk menatap langit dibawah pohon kelapa di teras belakang rumah saya. Terdengar suara bariton yang mengucap salam.
“As salamu alaikum,” sapanya. Saya pikir pak Aly, ternyata bukan.
Ah, ini dia orang yang tadinya akan menagih hutang dengan menantang saya.
Saya pun menjawab, “Wa alaikum salam.”
Tanpa basa basi, dia langsung bertanya, “Begini pak, utang bapak yang 10 juta, apa bisa saya ambil sekarang?”
Saya hanya berkata, “Anak saya sakit. Saya perlu uang untuk biaya anak saya. Sebentar lagi ada uang 3 juta datang, terserah mas mau ambil berapa, mas yg atur,” kalimat itu mengalir tanpa saya rancang. Marah saya sudah hilang, saya pasrah saja.
“Oh…, begitu ya pak,” katanya dengan nada datar. “Anak bapak sakit dua-duanya? Yang berbaring didalam itu?” tanyanya sambil mengedikkan kepala ke ruang tengan.
“Iya,” jawab saya singkat.
“Oh, maaf kalau begitu. Saya nggak tahu kalau anak bapak sakit. Sebaiknya bapak urus mereka. Uang saya gampang, saya pamit saja dulu. Besok-besok kabari saya, ya pak,” katanya tanpa diduga-duga.
Diapun pamit pergi dan saya masih dalam posisi bingung, lunglai diujung bangku dibawah pohon. Tubuh saya berkeringat. Saya memaksa diri untuk bangun dan mengikuti dirinya dari belakang sambil memanggilnya.
“Mas, saya pasti membayar utang saya. Saya hanya butuh waktu. Maafkan saya, ya mas. Kalau saya kasar atau panik,” kata saya. Ketika dia berbalik badan, saya julurkan tangan saya yang kemudian dia sambut dengan jabat tangan yang erat, senyum dibibirnya.
Dia pun berkata, “Iya pak, saya juga minta maaf.”
“Saya salah mas,” kata saya, “Saya berutang tapi tidak berkemampuan. Tapi saya janji mas, saya pasti bayar.”
Tak lama setelah dia pergi, datanglah pak Aly dengan Kijang tuanya. Tanpa basa-basi, langsung saya peluk erat dia. “Pak Aly, syukron ….. terima kasih,” kata saya.
“Ayo ke dokter, mas. Aku bawa Fathur, mas gendong Azka,” ajaknya singkat.
Setelah 2 tahun dihajar musibah yang merusak keyakinan saya, akhirnya saat itu saya menyadari satu hal. Semua masalah yang saya alami itu berasal dari diri saya sendiri, hal lain diluar diri saya hanyala pelengkap.
Saya langsung berdoa, “Maafkan saya ya Allah ….. ampuni saya. Engkau begitu mulia, dan saya selama ini salah memandang-Mu. Saya sadar bahwa saya sendirilah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan semua ini. Saya lah yang in charge sepenuhnya, maafkan saya telah meragukan kuasa-Mu, ya Allah.”
Saya memilih untuk berdamai dengan Tuhan, dan saya ingin memulai sesuatu dengan kesadaran penuh untuk mengubah nasib saya, menulis ulang sejarah hidup saya. Saya mendapat semacam pemahaman bahwa cara berpikir saya saat itu tidak bekerja dengan benar. Buktinya saya rugi. Buktinya saya bangkrut. Buktinya semua orang menjauh.
Artinya, saya harus merubah cara berpikir saya. Harus kemana dan bagaimana saya bisa mengubahnya? Itulah pertanyaannya.
Tak Lama setelah menjual rumah, saya pindah ke rumah kontrakan yang sempit. Suatu sore tetangga rumah kontrakan saya pulang dari kantor, kaca mobilnya terbuka separuh. Dia rupanya ingin membuang sesuatu mungkin sampah.
Agaknya dia tidak melihat saya yang berdiri disisi jalan tersebut. Mungkin karena Maghrib yang pencahayaannya mulai samar, mungkin juga dia tidak fokus karena sibuk mengumpulkan barang yang akan dibuangnya. Bruk… segumpal kertas jatuh tepat di kaki saya.
Entah mengapa saya tergerak untuk memungutnya. Mungkin karena saya tertarik dengan tulisannya yang berwarna merah mengkilat. Setelah membuka lipatannya, saya baca kertas itu ternyata merupakan brosur ‘Millionaire Mindset’ Training … di Australia.
Saya merasa aneh dan terkejut. Inikah jawaban dari doa yang saya panjatkan?
Saya berdiri termenung. Rupanya tetangga saya tadi baru sadar kalau sampah yang dibuangnya jatuh di depan saya. Dia pun menghampiri saya, “Mas, maaf aku nggak lihat,” katanya dengan kikuk.
“Lho, nggak apa-apa. Aku-nya juga lagi ngelamun, nggak ‘ngeh’. Aku baru ‘ngeh’ setelah melihat brosur ini,” kata saya berbasa basi sambil menunjukan lembaran tersebut.
“Iya, tadi saya dapat dari kantor. Tapi sepertinya nggak mungkin saya kesana. He he he… bukannya gak butuh jadi orang kaya, sih. Tapi harganya itu lho, buat seminggu saja Rp 30 juta. Mending juga buat modal dagang,” urainya.
Saya hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum sopan. “Saya pamit ya, Pak Syarif,” kata saya.
“Ya mas. Maaf ya tadi benar-benar nggak sengaja, mas,” katanya sungguh-sungguh.
“Nggak apa-apa bos, santai saja,” kata saya lagi.
Setelah itu saya langsung sibuk berfikir, dimana saya bisa cari uang Rp 30 juta? Belum lagi untuk sangu keluarga dirumah sementara saya pergi. Yang jelas, saya sudah bertekad untuk berubah dan saya melihat ini sebagai solusinya. Saya percaya itu.
Singkat cerita, harta terakhir saya yaitu Motor Tiger, Mesin Jahit dan beberapa barang keluarga, saya jual, saya nekat terbang ke Negeri Kangguru (Australia). Saya menginginkan ilmu tersebut. Saya pun berangkat untuk mengikuti ‘Millionaire Mindset’ Training disana dengan harapan bisa menerapkannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi saya disini.
Kira-kira sebulan setelah kembali dari pelatihan selama 7 hari tersebut, ternyata tidak ada perubahan apa-apa dalam perjalanan hidup saya. Saya masih menganggap bahwa apa yang saya pelajari itu agak aneh. Agak nggak kena dilogika.
“Mek ngono tok, opo iyo? Kayak gitu doang, memang bisa?” batin saya.
Memang benar. Saya meragukan dan saya menganalisis, mencoba mengurai maksud dari pelatihan tersebut, tetapi saya lelah. Keadaan saya masih begitu-begitu saja. Saya belum bisa dapat uang lagi, saya belum bisa melunasi tunggakan utang. Saya belum bisa merubah nasib saya.
Apakah saya harus belajar lagi?
Saya mencoba mengingat mundur pengalaman hidup saya. Semua itu terjadi hingga diusia 26 tahun. Benar, saya merasa seakan berjalan dijalan bebas hambatan. Semua mudah, semuanya gampang. Pada saat itu, saya bahkan ‘menggampangi’ proses yang saat ini justru proses merupakan hal yang paling saya hormati.
Barulah sejak usia 28 tahun, kehidupan saya mengalami pasang surut yang luar biasa. Baik dari masalah pribadi yang personal, masalah spritual ketuhanan, masalah rumah tangga, masalah Parenting hingga keuangan.
Dikala saya berfikir laut itu berair tenang, saya memilih mengangkat jangkar dan mengembangkan layar ke sebuah tujuan pasti, yaitu ingin sukses. Dengan tujuan hanya tahu satu arah, yaitu kedepan.
Sebuah kesombongan yang saya bayar sangat mahal. Sangat melelahkan, penuh duka, air mata dan keringat. Ternyata laut didepan tak semanis gelombang dipantai. Dalam perjalanan, ombak besar, angin kencang, bahan bakar kurang, sumber daya terbatas.
Satu hal yang saya lupa, saya tidak membawa kompas penunjuk arah.
Dalam artian, saya mengarungi samudera tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa pembimbing. Mentang-mentang punya Glory from the Past, kisah sukses masa lalu, saya merasa bisa melakukan apa saja.
Inilah biang masalah saya dimasa kedepannya sejak keputusan mengarungi samudera. Hingga sampailah saya dititik ketika kapal saya akhirnya karam ke dasar samudera, sementara badan saya terdampar di pulau kecil sendiri dengan kebutuhan dasar seadanya.
Saya hanya bisa diam. Meratap pun tidak bisa. Air mata habis. Tenaga tak punya. Yang ada hanya nafas dibadan, itupun setiap tarikan nafas terasa sesak. Seakan-akan dada ini mau meledak karena terisi oleh rasa kesal, lelah, marah dan kecewa.
Karena itu, ketika saya memutuskan untuk berubah. Artinya saya tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang sama seperti masa lalu. Saya harus melakukannya dengan cara yang berbeda.
Karena itulah saya memutuskan bahwa saya harus berimu agar saya memiliki platform atau pondasi baru, terutama untuk cara saya berfikir.
Ibaratnya, saya bukan hanya perlu belajar dan menginstall software baru. Tapi ‘OS’ atau Operating System-nya harus saya reset untuk bisa terhubung dengan software tersebut.
Sederhananya begini, jika otak kita yang kemampuannya sangat dahsyat ini adalah hardware pemberian Tuhan. Softwarenya kita sendiri yang pasang.
Sebut saja software sukses, software sehat, software bahagia, itu semua manusia yang install. Jadi, hardwarenya memang pemberian Tuhan, tetapi softwarenya buatan manusia.
Mungkin banyak pembaca yang berkerut ketika saya membawa-bawa hal ini. Tapi coba saya berikan ilustrasi. Seorang anak yang hidupnya dikritik, dimarahi, ditekan, dipaksa, diharuskan, dibatasi, dilarang, dimaki dan dihina akan membuat dirinya tumbuh sebagai pribadi yang peragu, pemarah dan pendendam.
Bandingkan dengan anak yang didorong, dipuji, disayang, diperhatikan, didukung dan dikelilingi suasana penuh canda tawa, sang anak akan memiliki platform hidup lebih ringan, ‘fun’ banyak senyum dan vibrasi dirinya disukai orang.
Yang saya maksud disini adalah, software seseorang diinstall oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dan, tentu saja software yang buruk bisa diganti, diubah bahkan dibuang bila kita mau. Sesuatu yang dipasang, umumnya bisa juga dilepas, bukan? Bukan sesuatu yang permanen, teman-teman dari bidang psikologi mungkin mengenal ini sebagai sesi ‘therapeutic’, istilah dalam dunia psikologi.
Ketika mencari kompas ilmu dan perubahan pola pikir itulah; baru saya sadar. Selama ini saya menerima hasil sebuah printer yang isinya salah, lalu saya mati-matian memberi ‘tip ex’ pada tulisan dalam kertas itu. Begitu seterusnya.
Saya tidak sadar bahwa yang harus saya ubah justru dokumen yang akan di-print, bukan yang sudah di-print. Yang salah bukan printernya, melainkan data didalam komputernya. Kalau isi komputernya sudah benar, baik itu software maupun datanya, hasil yang di-print pasti tidak akan salah.
Sumber : Buku SADAR KAYA
Karya : Mardigu Wowiek Prasantyo
Baca Tulisan Berikutnya : Jangan Membatalkan Doa